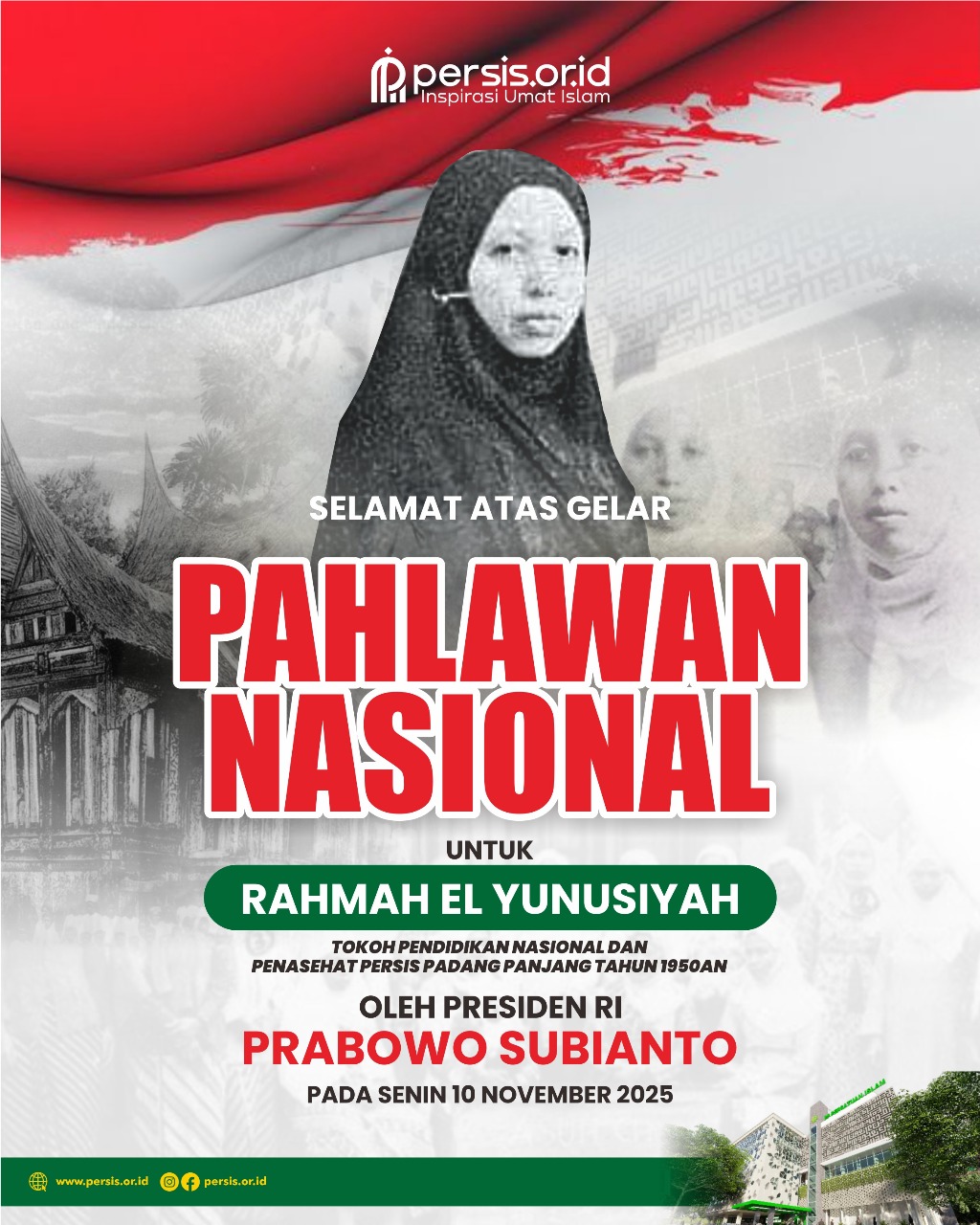Tinjauan Filosofis Konsep Adab dan Peranan Guru di Era Kontemporer
Oleh: Muhammad Luthfi Fathurrahman
Bid. Pendidikan dan Dakwah PP Ikatan Pelajar PERSIS
Pendahuluan
Krisis dalam ekosistem pendidikan kontemporer telah menjadi isu yang menuntut perhatian serius, khususnya terkait fenomena kekerasan yang mencerminkan hilangnya keselarasan fundamental antara pendidik dan peserta didik. Permasalahan ini melampaui dimensi regulasi atau Hak Asasi Manusia semata, namun harus dianalisis dari perspektif filosofis mengenai hilangnya nilai (adab) sebagai landasan. Paradigma pendidikan nasional saat ini dihadapkan pada tantangan integritas tujuan, di mana indikator capaian seringkali tereduksi pada aspek kognitif-utilitarian, mengabaikan pembentukan karakter dan budaya etis. Dalam diskursus Pendidikan Islam, fenomena ini berakar pada berkembangnya sekularisasi ilmu pengetahuan, yang secara perlahan menggeser nilai-nilai etis, ketuhanan, dan spiritualitas yang kental dalam tradisi pendidikan Islam.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, seorang filsuf dan pemikir pendidikan Islam terkemuka, dikenal karena kontribusinya yang fundamental dalam diskursus Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer. Inti dari proyek intelektual Al-Attas adalah tesis bahwa krisis peradaban Muslim modern berakar pada loss of adab (hilangnya adab). Dalam pandangan Al-Attas, adab merupakan komponen sentral dalam Islam, yang secara mendasar memengaruhi epistemologi dan praktik pendidikan. Esai ini bertujuan untuk melakukan tinjauan filosofis-analitis terhadap konsep adab yang diusung oleh Al-Attas, serta menganalisis secara deskriptif bagaimana konsep ini menempatkan peranan guru (mu'addib) sebagai pilar utama dalam proses ta'dib (pendidikan) untuk mengatasi sekularisasi ilmu.
Adab sebagai Inti Pendidikan Islam: Konsep Epistemologis
Berbeda dengan pandangan Barat yang sering memisahkan etika dari ilmu pengetahuan, Al-Attas menegaskan bahwa adab adalah prasyarat dan tujuan utama dari pendidikan Islam. Dalam karyanya yang seminal, Islam and Secularism (1993, hlm. 76), Al-Attas mendefinisikan adab sebagai disiplin diri dan tindakan yang benar, yang diwujudkan dalam penempatan segala sesuatu—termasuk ilmu pengetahuan, nilai, dan manusia—pada tempatnya yang benar di dalam tatanan eksistensi. Sederhananya adalah, adab merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan pada tempatnya. Dapatkah dimunculkan pertanyaan tentang mana yang benar? Barangkali jawaban itu ada dalam ilmu pengetahuan pembaca, sejauh mana memahami kebenaran yang dilandaskan pada Worldview of Islam.
Secara epistemologis, hilangnya adab bermakna hilangnya kemampuan membedakan antara ilmu yang benar (haq) dan ilmu yang salah (batil), atau antara prioritas dan sekunder. Al-Attas berargumen bahwa ketiadaan adab pada pelajar dan pendidik menyebabkan ilmu dipahami secara netral dan sekular, terlepas dari dimensi spiritual dan teologisnya. Krisis yang dihadapi oleh dunia Muslim, menurutnya, bukanlah krisis miskin ilmu, melainkan krisis ilmu yang salah arah, yang diakibatkan oleh kurangnya adab (Al-Attas, 1993). Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan Islam bukanlah sekadar mengajarkan, mengisi cangkir yang kosong, mendoktrin sesuatu untuk sesuatu, melainkan ta'dib, yaitu proses menanamkan adab, yang berujung pada pengenalan Tuhan dan tempat seseorang dalam skema ciptaan-Nya, menjadikan manusia menjadi paripurna akan diri dan sekitarnya.
Peranan Guru (Mu'addib) sebagai Agen Ta'dib
Apabila adab adalah esensi, maka guru memegang peranan vital sebagai agen utama yang mengimplementasikan ta'dib. Al-Attas tidak menggunakan istilah guru (ustadz) atau pengajar (mu'allim) secara eksklusif, tetapi lebih menekankan peran mu'addib—seseorang yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi yang mampu menanamkan adab.
Peranan mu'addib ini bersifat holistik dan mencakup dimensi intelektual, spiritual, dan moral. Ketiga dimensi ini sangat penting untuk keberlangsungan Pendidikan. Guru yang ideal harus memenuhi dua syarat utama: (1) memiliki ilmu yang benar (al-'ilm al-sahih) yang bersih dari elemen sekularisasi, dan (2) memiliki kepribadian yang luhur dan dapat dicontoh (qudwah hasanah) (Hashim, 2011, hlm. 89). Guru, dalam pandangan ini, adalah pewaris para nabi yang memiliki tugas suci untuk membimbing jiwa pelajar menuju kebenaran. Otoritas guru tidak hanya didasarkan pada kompetensi akademis, melainkan pada kepercayaan dan integritas moral yang mendalam. Pelajar harus memiliki adab terhadap guru—yaitu menghormati dan menghargai guru sebagai sumber ilmu dan moral—agar proses ta'dib dapat berlangsung secara efektif.
Relevansi Konsep Adab dan Guru dalam Konteks Kontemporer
Konsep Al-Attas mengenai adab dan guru memiliki relevansi krusial dalam sistem pendidikan kontemporer, terutama di tengah arus deras informasi dan desentralisasi otoritas pengetahuan. Di era digital, pelajar seringkali menganggap pengetahuan sebagai komoditas yang mudah diakses, yang dapat mengurangi penghargaan terhadap sumber dan transmisi ilmu.
Al-Attas menawarkan kritik terhadap model pendidikan yang berorientasi pada pasar dan utilitarianisme, yang menghasilkan pelajar cerdas tetapi miskin moral (Bakri, 2015). Peneladanan terhadap konsep mu'addib menuntut agar pendidik kembali berfungsi sebagai figur moral, bukan sekadar fasilitator data. Bagi pelajar, konsep adab mengajarkan pentingnya keseriusan (jiddiyyah) dan disiplin dalam menuntut ilmu, menyadari bahwa setiap pengetahuan membawa tanggung jawab etis. Dengan kembali menghargai adab dan otoritas moral guru, institusi pendidikan dapat mencegah disintegrasi identitas intelektual yang disebabkan oleh epistemologi sekuler.
Quo Vadis: Manifestasi Krisis Adab Guru dan Implikasinya dalam Pendidikan Indonesia
Konsekuensi dari sekularisasi ilmu dan hilangnya pandangan holistik terhadap pendidikan tampak jelas dalam berbagai kasus yang mencerminkan krisis adab di ranah pendidikan nasional. Jika Al-Attas mendefinisikan mu'addib sebagai teladan moral, realitas kontemporer sering menunjukkan deviasi signifikan dari idealisme tersebut. Krisis adab kini tidak hanya terbatas pada perilaku murid terhadap guru, tetapi juga sebaliknya.
Sebagai studi kasus, fenomena kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik seringkali disoroti media dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Meskipun niat awalnya diklaim sebagai bentuk penegakan disiplin atau 'pendidikan keras', tindakan kekerasan verbal, psikis, atau fisik yang dilakukan guru menunjukkan kegagalan fundamental dalam menjalankan peran mu'addib (Hashim, 2011). Contoh kasus Kepala Sekolah yang dilaporkan karena menampar siswa karena merokok (berita 2025) atau kasus guru yang melakukan kekerasan fisik di sekolah telah menjadi sorotan publik yang intens (KPAI, 2018). Tindakan ini jelas bertentangan dengan konsep qudwah hasanah (keteladanan yang baik) yang disyaratkan oleh Al-Attas.
Secara analitis, kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa otoritas guru yang berbasis pada adab dan kasih sayang telah digantikan oleh otoritas yang didasarkan pada kekuasaan dan regulasi (Otoritarianisme Pedagogis). Ketika guru gagal menempatkan dirinya sebagai pembimbing spiritual dan moral, ia otomatis gagal dalam tugas ta'dib. Implikasinya, menurut Al-Attas, adalah generasi pelajar yang meskipun mungkin disiplin karena takut, gagal memahami esensi adab sebagai disiplin diri yang berakar pada kesadaran spiritual. Ini memperburuk krisis etika, di mana ilmu yang ditransmisikan kehilangan keberkahannya karena tidak didasarkan pada fondasi adab yang kokoh.
Kesimpulan
Syed Naquib Al-Attas menyediakan kerangka filosofis yang kokoh untuk memahami adab sebagai fondasi peradaban Islam dan pendidikan yang benar. Adab, bagi Al-Attas, bukanlah sekadar etiket sosial, tetapi sebuah prinsip epistemologis yang menentukan validitas ilmu. Konsep ini secara mutlak menempatkan guru (mu'addib) sebagai sosok sentral yang bertugas melakukan ta'dib, yaitu menanamkan adab agar pelajar dapat menempatkan segala sesuatu secara benar. Meneladani visi Al-Attas berarti menyerukan reformasi pendidikan yang mengembalikan nilai-nilai spiritual dan etis ke dalam kurikulum, memastikan bahwa generasi pelajar kontemporer tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga beradab dan bertanggung jawab secara moral. Krisis pendidikan, yang termanifestasi dalam kasus hilangnya adab guru terhadap murid, adalah krisis moral, dan solusinya terletak pada pembinaan adab yang otentik.
Daftar Pustaka
Al-Attas, S. M. N. (1993). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ISTAC.
Bakri, S. (2015). The Concept of Adab in Syed Muhammad Naquib Al-Attas’s Philosophy. Gombak: IIUM Press.
Hashim, R. (2011). Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory and Practice. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
BACA JUGA:IPP PERSIS Tasikmalaya Gelar ROFI 1 Vol 2, Cetak Kader Kritis dan Responsif